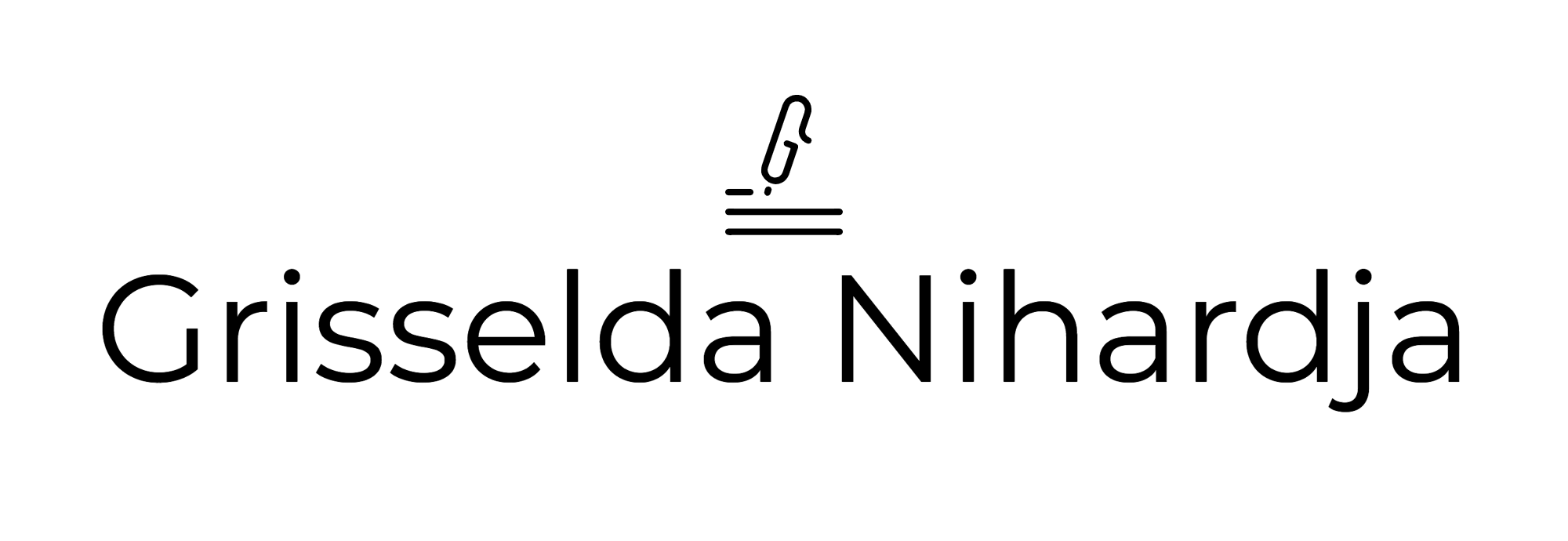Unfollow: Cerita Nyata Seorang Mantan Ekstremis yang Patut Digubris
Membaca Unfollow: A Journey from Hatred to Hope yang ditulis Megan Phelps-Roper nggak ada sama sekali dalam rencana saya bulan ini. Saya nggak tahu dia siapa, nggak pernah lihat juga bukunya dibaca oleh teman-teman saya. Murni hasil dari iseng browsing di Kindle Books. Judul bukunya bikin saya ingin tahu lebih, jadi baca sinopsisnya, eh kok rasa penasaran saya makin terpanggil. Jadilah ini saya baca sampai selesai.
Dari buku ini, saya baru tahu tentang Westboro Baptist Church, gereja di Amerika Serikat yang ternyata dikenal sebagai gereja yang punya cap sering menyebarkan kebencian. Kalau lihat rangkaian aktivitasnya, ya jadi paham kenapa cap itu melekat. Mereka sering picketing (protes dengan membawa sign), dan sengaja mengincar komunitas tertentu. Mereka bisa “muncul” di pemakaman tentara dengan intensi menghakimi orang-orang berdosa. Pemahaman anggota WBC adalah musibah apa pun yang terjadi, itu karena orang-orang berdosa (LGBTQ+, perzinahan, percabulan, penyembahan berhala, dsb. Agama lain seperti Katolik, Jewsih, Islam, Kristen, pun dianggap manusia-manusia berdosa. Kalau kepercayaannya berbeda, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai ajaran yang dianut mereka, dianggap sesat dan bakal masuk neraka). Dan sebagai umat Allah yang maha benar (uhuk), mereka merasa wajib mengingatkan orang-orang yang masih hidup untuk bertobat. Walau caranya dengan teriak-teriak di pinggir jalan, dan dengan membawa papan tulisan yang kata-katanya bisa menyakiti orang lain.
Buku ini adalah memoir Megan Phelps-Roper, cucu dari pendiri WBC. Di buku ini Megan menceritakan bagaimana dia dibesarkan di tengah keluarga besar WBC, dan apa yang membuatnya akhirnya meninggalkan WBC sekaligus keluarganya. Semua ketakutan, rintangan, kekhawatiran, dan bagaiamana pola pikirnya terurai dan sudut pandang sempitnya terbuka sedikit demi sedikit dituturkannya dengan apik di buku ini.
Sedari awal membaca, Megan sudah mengenalkan rutinitas yang ada di keluarganya. Apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Mau nggak mau saya menyangkut pautkan cerita ini dengan peran keluarga, terutama orang tua, yang sangat penting untuk seorang anak.
Ini mengingatkan saya dengan buku The Four Agreements yang ditulis Don Miguel Ruiz (ulasannya bisa dibaca di sini). Di buku itu, Don Miguel Ruiz memperkenalkan konsep persetujuan dan domestikasi manusia. Sedari lahir, anak nggak punya pilihan. Nggak bisa memilih siapa orang tuanya, nggak bisa memilih mau lahir di keluarga yang mana, nggak bisa memilih mau punya kepercayaan apa. Semuanya sudah ada sebelum anak lahir. Anak cuma bisa percaya dan setuju dengan apa yang orang tuanya ajarkan. He even said children are domisticated the same way that we domesticate a dog, a cat, or any other animals. Pakai metode reward and punishment. Karena dihukum nggak enak, dan dikasih hadiah enak, biar hidup “enak”, terbiasa tumbuh besar sambil menyesuaikan dengan apa yang si pemberi hadiah mau, atau hidup menyesuaikan dengan pemegang kekuasaan di komunitasnya mau (pemimpin gereja dan orang tua).
Tumbuh besar, anak belum bisa memiliki atau paham konsep berpikir yang mandiri. Pasti beberapa tahun pertama diarahkan oleh orang tua. Membantu orang tua baik, melawan orang tua nggak baik. Kalau ada orang bilang gini, jawabnya gini. Sampai kapan diarahkannya, tergantung orang tua dan anaknya. Ada anak yang pada akhirnya bisa berpikir mandiri, ada juga anak yang dididik untuk tidak bisa mandiri agar bisa dikontrol orang tua. Selalu ada variasi lain yang bisa kita temukan di luar keluarga kita masing-masing.
In terms of extremist family, saat nggak ada orang yang rutin untuk challenge kepercayaan mereka, kehidupannya akan seperti rantai yang terus menyambung: Ekstremis mendidik ekstremis. Anak ekstremis tumbuh besar, punya keluarganya sendiri, dan mendidiknya anaknya menjadi ekstremis juga. Itu adalah satu-satunya ajaran yang mereka tahu, satu-satunya ajaran yang mereka dapatkan sedari kecil. Doktrin itu yang diperkenalkan dan ditanamkan dengan kuat sedini mungkin. Seperti tradisi cuci otak jangka panjang yang diwariskan turun-temurun.
Setelah membaca memoir ini, ada ciri-ciri komunitas ekstrem yang “diwakili” oleh WBC. Beberapa tandanya:
Selalu merasa benar.
Arogan. Tidak menerima kritik, tidak mau mendengarkan, sulit diajak berdialog. Tipe ekstremis nggak kenal istilah agree to disagree. If you’re not with me, then you’re my enemy.
Kekuasan bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat.
Pemimpin berhak menentukan, mengambil keputusan, tanpa mengindahkan concern dari anggotanya.
Patriarki.
Suara wanita dititipkan ke ayah atau suaminya. Saat ingin mengutarakan pendapat yang berhubungan dengan gereja dan kepercayaannya, alurnya seperti itu.
Tameng dan senjata terbaik: Ayat kitab suci.
Selalu ada ayat yang dipakai sebagai landasan protes, menghakimi orang, sampai mendoakan orang berdosa agar hancur/meninggal.
Gaslighting yang dianggap wajar.
Malah disepakati, terutama oleh jajaran pemimpin. Ketahuan “dosa”, pasti dihukum, dikucilkan, diisolasi. Dimanipulasi sedemikian rupa sampai orangnya merasa memang dia yang salah, bukan doktrin dan lingkungannya yang sakit.
Munafik.
Karena ujung-ujungnya banyak inkonsistensi dari doktrin yang dijalani. Misalnya, menjalani mentah-mentah ayat A, tapi ayat B nggak mau dilihat karena memunculkan kontradiksi dengan ayat A. Saat menghadapi kontradiksi, apa yang bertentangan itu nggak dijawab. Saat Megan ditanya seperti ini, dia pun mengakui ada yang aneh dengan posisi gerejanya.
“That’s one thing I have never understood about your family. They’re all lawyers, right? The U.S. Constitution was written some two hundred years ago in essentially modern English, and there’s so much disagreement about how the U.S. Supreme Court should interpret and apply those words today. The Bible was written thousands of years ago in languages no one speaks anymore ... and somehow, Westboro alone has figured out its one true meaning?” Articulated that way, the arrogance of our position seemed even more incomprehensible.
Alkitab punya banyak versi/tafsiran. Saya cek di bible.com, yang bahasa Inggris sendiri punya 61 versi. Kata-katanya bisa beda, ada yang lebih asertif, ada yang lebih lembut, ada yang terasa kaku, ada juga yang sudah diterjemahkan ke bahasa yang modern. Dari masing-masing versi, intepretasinya bisa beda lagi untuk tiap orang. Saat saya menyimpulkan pengertian akan satu ayat, bisa jadi kamu pengertian yang berbeda.
WBC menggunakan alkitab versi King James yang sejujurnya sulit dibaca. Mereka hanya menganggap versi King James ini yang valid dan perlu diikuti. Jujur, pusing saya membaca referensi bahasa archaic yang jadul.
Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself. -
Leviticus 19:17
Kalau dalam bahasa Indonesia versi Terjemahan Baru:
Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegor orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia.
Imamat 19:17
Satu ayat inilah yang jadi modal WBC untuk membenarkan picketing dan “nyerang” sana-sini. Pegangan mereka ada di kata kunci rebuke = to criticize sharply.
“As long as we believed our words to be truthful, we were free to rebuke the rest of the world at any time, in any place, and in any way that we wanted. We could be harsh, and crude, and insulting, and it didn’t matter, because everyone else was Hell-bound anyway. Those verses justified almost everything we did— including picketing funerals.”
Sedangkan “musuh” perang di Twitter-nya Megan, yang sekarang jadi teman, menyampaikan ayat yang sama dari versi kitab sucinya (Jewish).
“From our view,” David said, “a rebuke is supposed to happen privately, kindly, and with people you have reason to believe will hear you. If you’re attacking someone you know won’t listen—if you’re trying to correct them harshly, in a way that will provoke them to anger instead of encouraging them to change their ways—then you’re the one who is committing a sin.”
By any means, I’m not Jewish, but I will choose their version for this particular verse 100%.
That’s humanity in there. Memanusiakan manusia.
Saya yakin nggak gampang buat mempelajari kitab suci. Nggak semua orang punya niat buat benar-benar mempelajari, menelusuri, sekaligus memahami konteks satu kitab suci setebal itu, dan menggali informasi dari tiap-tiap “buku”. Hapal saja nggak cukup. Yang perlu dicek kan pemahamanannya. Apakah sudah tahu penulis ayat tersebut saat itu berada dalam kondisi seperti apa, kota tempat tinggalnya lagi bagaimana, dan tujuan dia menulis ayat itu untuk apa? Setiap penulis pasti punya intensi. Menulis bukunya untuk apa. Apakah ada suatu pembelajaran yang bisa kita petik dari ribuan tahun lalu yang bisa dipakai di zaman sekarang? Andai, ada ayat yang mendukung tindakan A, tapi beberapa buku kemudan ada rasul lain bilang B, dan kedua ini berbeda, mana yang perlu diikuti? Lagi-lagi: Nggak gampang, perlu ketekunan, dan ketelitian :)
Selalu ada ruang untuk berdialog dengan lebih sopan. We’re mirroring each other in a way. Saat berhadapan dengan orang yang santai dengan tutur katanya sopan atau lucu, kita bisa terbawa seperti itu juga. Begitu juga sebaliknya. When we’re being too offensive, there are always people out there that will have reasons to fight us back. They’re mirroring what we do to them.
Bukan berarti ekstremis nggak punya harapan. Megan justru jadi bukti nyata kalau harapan itu jelas-jelas ada. Untuk “menyentuh” seseorang yang tumbuh besar di lingkungan ekstrem, perlu ada orang lain yang sabar dan rajin mengetuk pintu hati dan pikirannya, menciptakan ruang yang aman untuk berdiskusi, bertanya, sekaligus bertukar opini. It’s a collective work.
Saya salut dengan Megan yang akhirnya bisa lepas dari WBC. I can’t imagine how hard it was to leave your belief and family at once. Saya kagum dengan teman-teman Megan di Twitter yang walaupun punya kepercayaan berbeda, bisa memberikan argumen dan diskusi sehat yang menghasilkan dampak luar biasa buat hidupnya.
Tendensi ekstrem ini rasanya familier juga di area lain. Nggak hanya ada di agama, tapi juga ada di ranah politik, bisnis, ras, dan gender. Di Ted Talks-nya, Megan menyampaikan empat kunci saat menghadapi ekstremis yang dilakukan oleh teman-temannya di Twitter yang berpengaruh besar pada perubahannya:
Jangan berasumsi intensi negatif.
Megan mengingatkan kalau ekstremis dibentuk dan mengira kalau apa yang mereka perbuat adalah yang paling benar. They do what they do, because they think they can stop people from doing sin.
Tanya.
Ini supaya ada pemahaman apa yang melandasi pihak tersebut melakukan sesuatu. Selain itu, dengan bertanya, kita mengirim sinyal kalau mereka didengarkan.
Stay calm.
Berargumen dengan emosi nggak akan menghasilkan apa-apa.
Buat argumen.
Argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Argumen nggak perlu disampaikan dengan “panas”. Berargumen adalah menyampaikan alasannya. Kalau nggak dibilang, akan susah buat ekstremis untuk lihat ada argumen lain.
This is a wonderful book. Buku ini berhasil buat saya berkaca. Walau menurut saya, apa yang dijalani dan dipercayai nggak ada di level ekstrem, sangat menantang untuk benar-benar membuka mata, menengok ke sekitar dan melihat yang ada. Am I fooling myself by thinking that I’m always right?
Kalau kalian penasaran untuk tahu ceritanya, namun sungkan baca atau akses ke bukunya sulit, bisa tonton dulu video-vdieo wawancaranya. Ada banyak yang bisa ditemukan di YouTube, salah satu yang saya suka adalah interview-nya dengan Joe Rogan.
“Each one of us contributes to the communities, and the cultures and the societies that we make up. The end of this spiral of rage and blame begins with one person who refuses to indulge these destructives, seductive impulses. We just have to decide that it’s going to start with us.”