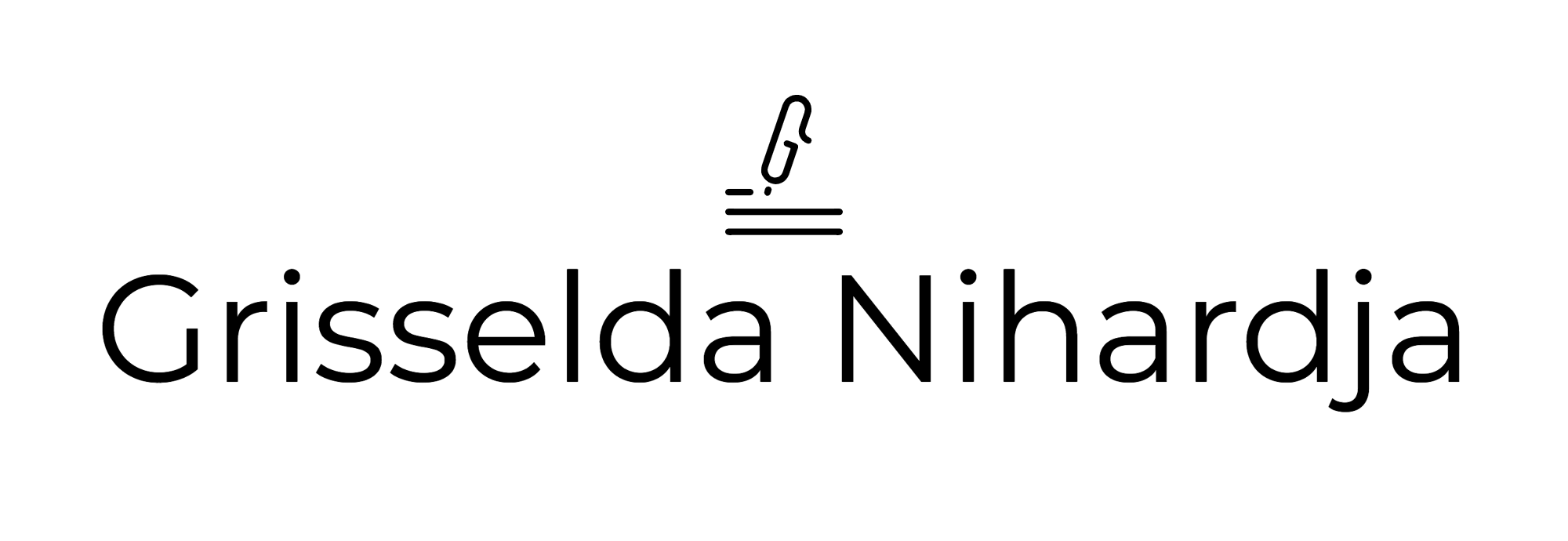Review Buku dan Film Kim Ji-yeong, Born 1982
Ada cerita tentang perempuan yang dibesarkan di keluarga yang mengharapkan anak laki-laki. Tumbuh besar, ia melihat dan merasakan berbagai kesempatan yang dirampas karena dirinya adalah seorang perempuan. Itu adalah beberapa potret yang ditunjukkan dalam buku dan film Kim Ji-yeong, Born 1982.
Novel yang ditulis oleh Cho Nam-joo ini terbit pertama kali di Korea Selatan pada 2016, dan sekarang sudah bisa kita temukan buku terjemahannya dari penerbit Gramedia dalam Bahasa Indonesia. Film-nya disutradarai oleh Kim Do-young dan sampai tanggal post ini tayang, masih diputar di CGV, dan Cinemaxx. Novelnya menuai kontroversi karena dianggap sebagai novel feminis (Padahal kenapa kalau feminis? Sila baca 10 pemahaman keliru tentang feminisme di sini). Namun, terlepas dari semua kontroversi yang muncul, tak menghalangi jalannya menjadi buku best-seller dan menjadi film box office.
Saya sudah menamatkan bukunya, juga sudah menonton filmnya. Ada dua versi cerita yang sudah saya kantongi. Di buku, ceritanya dikemas dengan sederhana. Dibuka dengan pengenalan Kim Ji-yeong dan situasinya yang baru memiliki anak berusia satu tahun. Pada bab-bab berikutnya, pembaca diajak mundur dan dan mengikuti cerita tokoh utama ini mulai dari kecil, usia sekolah, kuliah, bekerja, menikah, sampai memiliki anak. Sepanjang novel, saya diajak menyaksikan apa yang Ji-yeong hadapi di tengah masyarakat yang masih lekat dengan budaya patriarki.
Tak bisa dihindari, muncul kegetiran saat saya membaca novel ini. Perempuan yang seharusnya bisa normal, makin lama makin kehilangan "dirinya" dan memiliki depresi karena konstruksi sosial di sepanjang hidupnya. Tak bisa dipungkiri, muncul juga rasa marah saat menamatkan ceritanya. Walau ceritanya di Korea, banyak situasi yang terasa sangat realistis dan dekat juga di Indonesia. Untuk orang yang tidak bisa iya-iya saja saat melihat sesuatu yang tidak adil, sungguh, gemas sekali saya membacanya.
Novel ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang sederhana dan lugas. Tidak ada kata-kata puitis maupun kalimat yang penuh dengan "bunga-bunga". Tapi justru di sinilah daya pikatnya. Ceritanya tersampaikan dengan jelas tanpa terlalu diberi banyak bumbu. Sekali sudah baca, kemungkinan besar kalian juga akan terpikat dan sulit untuk melepas bukunya.
***
Berbeda dengan buku yang kronologinya lebih urut, alur di filmnya lebih sering maju mundur. Walau begitu, bukan berarti filmnya terasa kurang. Buat saya, filmnya juga bagus. Meski banyak setting waktu yang loncat ke sana dan ke sini, ceritanya tetap dikemas dengan apik dan bisa dinikmati.
Filmnya dibintangi dengan aktor dan aktris yang sudah tidak asing lagi di industri hiburan Korea. Dua tokoh utamanya adalah Jung Yoo Mi sebagai Kim Ji-yeong, Gong Yoo sebagai Jeong Dae-hyeon (suami Kim Ji-yeong). Saya juga salut bukan main dengan akting Kim Mi Kyun yang memerankan ibu dari Kim Ji-yeong. Kalau harus kasih nilai, akting mereka layak dapat A+ semua. Segitu bagusnya.
Kim Ji-yeong Born 1982 Movie
Perbedaan antara buku dan film yang paling menonjol adalah Jeong Dae-hyeon (suami Kim Ji-yeong) punya porsi yang lebih banyak di film. Ada beberapa adegan yang fokusnya menyoroti Dae-hyeon sebagai suami, dan kontribusinya sebagai partner istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sementara di buku, fokus utama ada di Kim Ji-yeong, dan Dae-hyeon hanya muncul beberapa kali.
Perbedaan lain yang tak kalah menariknya adalah akhir cerita. The movie ends with a hope. Sementara akhir cerita di novel terasa lebih dark. Dua versi ini tetap perlu diapresiasi karena walau bagaiamanapun, akhir cerita buku dan film dapat mewakili dua dari berbagai kemungkinan yang dihadapi perempuan dalam hidupnya. Untuk mendapatkan lebih banyak sudut pandang dan juga cerita yang lebih kaya, coba deh baca buku dan juga tonton filmnya mumpung masih tayang.
***
Di sepanjang cerita Kim Ji-yeong, Cho Nam-joo memperlihatkan konstruksi sosial tentang gender yang masih ada di Korea. Ada cerita Kim Ji-yeong yang pulang ke rumah sepulang kursus, dan ia diikuti murid laki-laki yang satu tempat kursus dengannya. Saat dijemput ayahnya di halte bus tempat ia turun, Ji-yeong sudah dalam keadaan menangis karena ketakutan. Tapi Ji-yeong justru dimarahi. Kenapa harus kursus di tempat sejauh itu? Kenapa ia berbicara kepada sembarang orang? Kenapa ia memakai rok sependek itu? LHA? Mirip banget ya? Di Indonesia, perempuan kena catcall, yang disalahkan perempuannya. Yang disalahkan atribut yang dipakainya. Kenapa pakai rok mini? Kenapa pakai baju terbuka? Padahal tidak ada hubungannya pakaian yang dipakai dengan aksi pelecehan pelaku. Jangan sekali-kali kepedean merasa diundang untuk melakukan hal tak pantas karena melihat pakaian yang dikenakan orang lain. It's plainly disrespectful.
Diskriminasi di tempat kerja juga dipotret dengan jelas di buku dan filmnya. Rekan kerja laki-laki mendapatkan promosi begitu saja, sedangkan Kim Ji-yeong dan teman-teman perempuan yang kinerjanya bagus sengaja diacuhkan. Ada teman perempuannya yang akhirnya mendapat promosi, itu pun setelah "menunggu giliran" sampai bertahun-tahun. Kalau teropongnya kita geser ke Indonesia, ada informasi tentang gaji buruh yang dibuka ke publik dari Badan Pusat Statistik Agustus 2019: Upah buruh pria Rp3,17 juta, sedangkan upah buruh wanita Rp2,45 juta. Geser lagi ke benua lain, di Amerika, ada studi Women in Workplace yang dilakukan berkala selama 5 tahun. There are improvements, but still, "women continue to be underrepresented at every level". Masih ada anggapan perempuan hanya cocok sebagai warga kelas dua. Masih ada anggapan bahwa merekrut perempuan merepotkan, apalagi bagi yang sudah berkeluarga, hamil, dan memiliki anak.
Kondisi perempuan yang sudah menikah juga diceritakan dengan gamblang oleh Cho Nam-joo. Tuntutan dari keluarga untuk memiliki anak tumpah ruah ke pundak Kim Ji-yeong. Suaminya sebenarnya baik, tapi caranya untuk meringankan beban Ji-yeong adalah dengan mengajaknya lebih cepat memiliki anak. And it didn't solve the problem, it just added more problem into their plate. Ji-yeong tahu betul keputusan untuk memiliki anak tidak bisa dianggap mudah dan terburu-buru. Ada perubahan dan pengorbanan yang perlu dilakukan, dan porsinya akan lebih banyak jatuh di "piring" perempuan. Badan siapa yang berubah? Siapa yang merasakan sakit dan ketidaknyamanan selama 9 bulan mengandung? Siapa yang merasakan sakit pasca melahirkan? Siapa yang harus bangun 2 jam sekali untuk memberi ASI? Siapa yang melepas karirnya untuk merawat anak tanpa jaminan bisa kembali bekerja? Apa yang berubah dari suaminya? Melepas jam nongkrong dengan teman-temannya, tidak bisa ikut sering-sering acara kantor, membantu pekerjaan rumah sepulang dari kantor.
"Kim Ji-yeong berusaha memahami alasan Jeong Dae-hyeon, tapi gagal. Alasan-alasan yang dilontarkan suaminya tadi sepertinya masih terlalu sepele jika dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang akan dialami Kim Ji-yeong sendiri.
Kim Ji-yeong tidak sanggup menyingkirkan perasaan tidak adil dan kehilangan yang menyergap dirinya." - Halaman 136 dan 137.
It's heartbreaking to see how Ji-yeong kept it all inside. Dia tahu kalau dirinya berada di tengah masyarakat dan lingkungan yang misoginis. Ada momen di mana Ji-yeong berani bersuara, namun lebih banyak Ji-yeong memilih untuk diam dan menerima. Dari awal, kesannya terlalu dark, ya? Tapi, tidak semua bagian dalam cerita ini getir, kok. Saya menghargai adanya beberapa karakter perempuan di cerita yaitu atasan, (mantan) teman kantor, kakak perempuan, dan ibu Ji-yeong yang bisa dan berani bersuara. Mereka berhasil menjadi contoh baik bahwa ada wanita yang mau mengambil bagian dan mewakili wanita lain yang kehilangan suaranya.
***
Bagaimana di Indonesia? Apakah masih ada budaya patriarki? Saya tidak bisa mewakili seluruh wanita di Indonesia, karena kita terdiri dari banyak suku, ras, dan agama. Saya tidak tahu tradisi adat masing-masing suku, juga agama lain. Saya hanya bisa menyampaikan cerita saya, dan apa yang saya lihat di lingkungan sekitar saya.
Yang masih saya dengar dan sukses bikin gemas bukan main adalah lelucon seksis. Ucapannya ini beragam, bisa membawa bentuk tubuh perempuan, sampai yang jelas-jelas bernada seksual. Biasanya, kalau dikonfrontasi, pelaku akan ngeles "Kan cuma bercanda." atau balik defensif dan ngatain perempuan terlalu sensitif. Bercanda itu ada batasnya. Kalau sudah seksis, maksudnya apa? Mau mengintimidasi? Mau menunjukkan posisi laki-laki yang menurutnya lebih berkuasa dari perempuan? Kalau mau mengkrabkan diri, pakai logika dari planet mana sih sampai berpikir perempuan kalau dibercandakan seperti itu jadi mau dekat-dekat? FYI, lelucon seksis ini tergolong pelecehan seksual, ya. Kalau terjadi pada kalian, jangan diam saja. Kalau teman kalian yang melakukan, tegur dan ingatkan. Kalau tahu teman kalian jadi korban, bantu dan tenangkan. Kalau terjadi di lingkungan kerja kalian, jangan ragu untuk adukan ke HRD atau atasan untuk ditindak lanjuti. Cek pedoman dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di sini. Jangan membiarkan sesuatu yang salah jadi wajar.
Berikutnya adalah ucapan "istri harus pandai mengurus suami". Dan ini yatuhanyaallahyhalord sering sekali saya dengar. Dari kenalan yang tidak begitu dekat, sampai ada anggota keluarga yang bilang seperti itu. Saya tahu dan sadar betul kondisi tiap orang dan tiap rumah tangga itu berbeda. Jadi tidak bisa dibandingkan, dan tidak bisa dipukul rata. Yang mengganjal, kenapa ya saya nggak pernah dengar ucapan suami juga harus pandai mengurus istri? Kenapa yang sering ditekankan dan diulang-ulang terus menerus dari sisi istrinya saja? Tanggung jawab suami seakan cuma satu: Cari duit. Selesai. Sementara tanggung jawab istri: memastikan ada makanan, membersihkan rumah, cuci-jemur-setrika pakaian, mengurus anak buat yang sudah punya, melayani suami dengan baik. Istri sama asisten rumah tangga kalau gitu jadi beda tipis, bukan? Tanggung jawab atas rumah tangga dan anak perlu dibagi rata dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing pihak. Beda loh, melakukan sesuatu karena tulus, dengan melakukan sesuatu karena dapat tekanan. Kalau tulus dan enjoy menjalani yang selama ini dilakukan, go on. Kalau merasa porsinya sudah berat sebelah, speak up.
Cerita Kim Ji-yeong terasa sangat dekat karena tak bisa dipungkiri kalau gender, sampai saat ini, masih sering dipakai untuk mendikte hidup seseorang. Perempuan mestinya begini, laki-laki mestinya begitu. Perempuan harus menikah, pintar mengurus suami, dan memiliki anak, baru dianggap perempuan yang utuh. Laki-laki harus kuat, tidak boleh menangis, tulang punggung keluarga, membayar semua kebutuhan dan keperluan hidup, baru dianggap laki-laki sejati.
"Imagine how much happier we would be, how much freer to be our true individual selves, if we didn’t have the weight of gender expectations."
Chimamanda Ngozi Adichie
Tidak banyak cerita yang bisa menyoroti dan menyingkap portret perempuan dalam fase-fase hidupnya setransparan ini. Cerita Kim Ji-yeong mewakili banyak perempuan, yang masih sering ditekan, dan terlalu sering kondisinya diwajarkan. Setidaknya dengan cerita ini, ada mata dan pikiran yang semakin terbuka, bahwa ada perubahan yang harus dilakukan, dan perlu ada suara yang berani mewakili sesama. Budaya, yang baik maupun yang buruk, diciptakan oleh manusia, dan karena itulah manusia juga yang bisa mengubahnya. Bersama-sama.